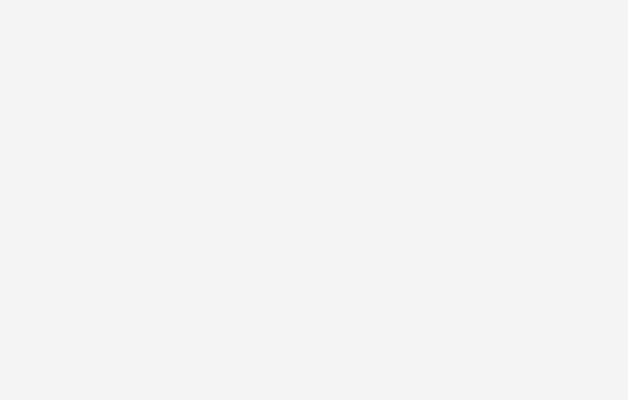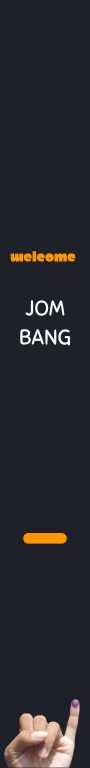Ruang Aman Bernama Musik: Kegelisahan Kolektif dalam Playlist Re;torika
Jombang, 11 Januari 2025 – “Suara kami hanya dianggap statistik perhitungan angka, yang diombang-ambingkan disetiap pemilu tanpa pernah didengar, dianggap, apalagi dijadikan acuan kebijakan. Aspirasi kami ditolak mentah-mentah, suara kami […]
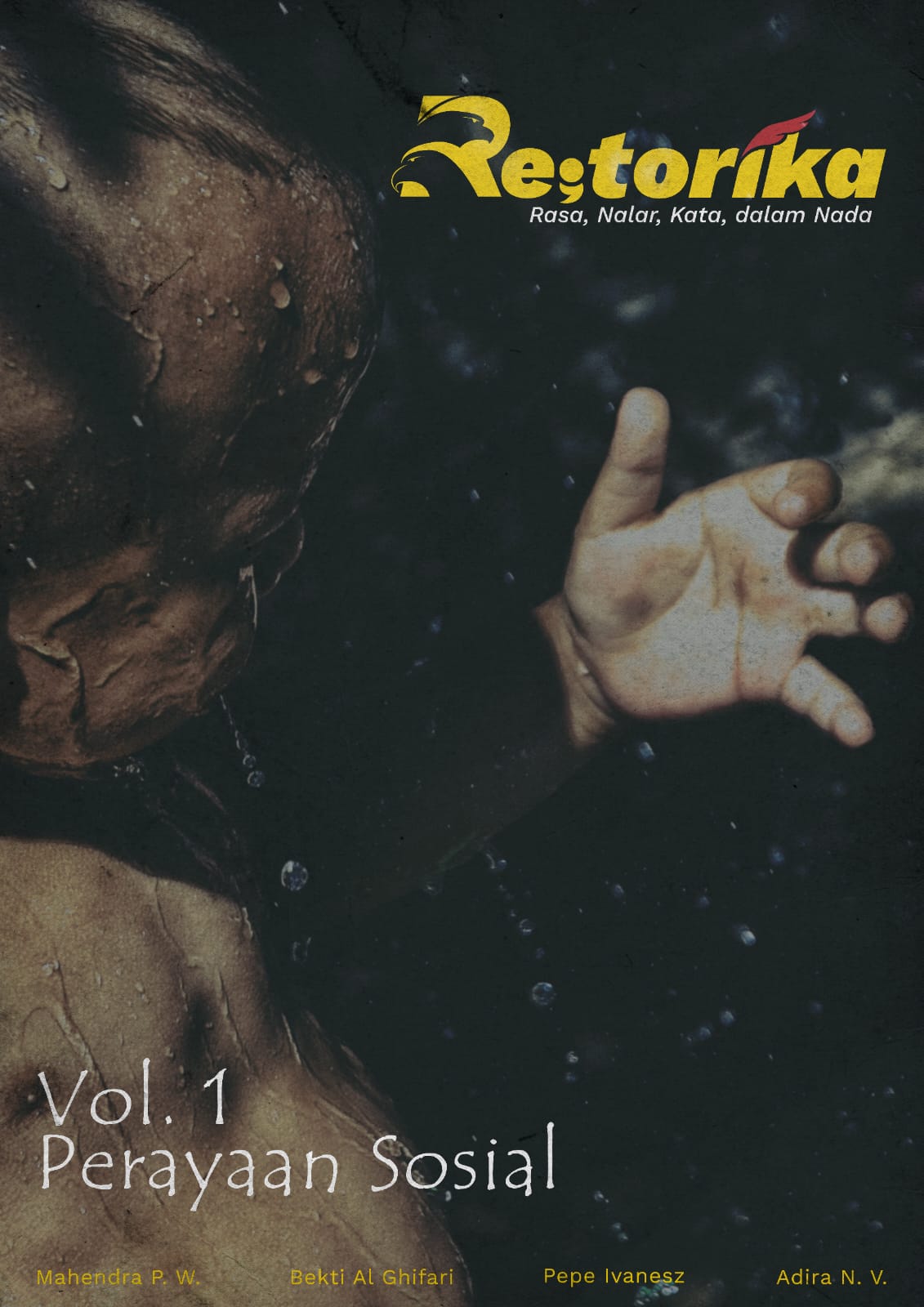
Jombang, 11 Januari 2025 – “Suara kami hanya dianggap statistik perhitungan angka, yang diombang-ambingkan disetiap pemilu tanpa pernah didengar, dianggap, apalagi dijadikan acuan kebijakan. Aspirasi kami ditolak mentah-mentah, suara kami disumpal atas nama takhayul kebebasan pertanda apa?”,
Lorong Sepi, Re;torika
Di tengah hiruk-pikuk sosial Indonesia yang dipenuhi gaduh politik, kelelahan akibat banjir informasi digital, serta relasi sosial yang kian toksik dan saling mencurigai, kata-kata resmi sering terdengar hampa dan pidato publik kehilangan daya sentuhnya. Dalam situasi semacam ini, musik indie hadir bukan sekadar sebagai hiburan pelarian, melainkan sebagai ruang aman untuk berkata jujur. Jujur tentang lelah, marah, takut, dan harapan yang tak terwakili oleh bahasa kekuasaan. Melalui lirik-lirik yang sederhana namun tajam, lagu-lagu indie menyuarakan kegelisahan personal yang ternyata dialami bersama, menjelma menjadi cermin kolektif atas kondisi sosial yang rapuh. Di sanalah musik menjadi lebih jujur dari pidato: ia tidak menggurui, tidak memerintah, tetapi mengajak pendengarnya untuk berhenti sejenak, merasakan, dan merefleksikan luka sosial yang sering disembunyikan di balik kebisingan.
Musik indie tumbuh dan bertahan di luar arus utama, jauh dari kepentingan industri yang kerap menuntut kepatuhan pada selera pasar dan logika keuntungan. Posisi ini memberi kebebasan bagi para musisinya untuk bersuara tanpa harus menyamarkan kegelisahan mereka menjadi slogan kosong atau jargon yang mudah dijual. Kritik sosial dalam musik indie lahir dari pengalaman hidup yang nyata dan intim: tentang upah yang tak cukup, relasi yang timpang, rasa terasing di kota, hingga kelelahan mental yang sunyi. Lirik-liriknya tidak berteriak, tetapi berbisik jujur, seolah mengajak pendengar duduk sejajar dan mengakui bahwa ada yang tidak beres dalam cara kita hidup bersama.
Jika pada era sebelumnya kritik sosial identik dengan protes jalanan, spanduk besar, dan orasi lantang di ruang publik, kritik hari ini sering muncul dari ruang-ruang kecil dan personal. Ia lahir di kamar kos yang sempit, didengarkan lewat headphone sambil menatap layar ponsel, lalu disebarkan melalui media sosial sebagai potongan perasaan yang resonan. Pergeseran ini tidak membuat kritik menjadi lebih lemah, justru ia menjadi lebih dekat dan membumi, karena berangkat dari keseharian yang dialami banyak orang namun jarang diucapkan. Musik indie menjadi penanda zaman: kritik sosial yang tidak selalu meledak-ledak, tetapi meresap perlahan ke dalam kesadaran, membentuk kepekaan baru terhadap realitas yang kita hadapi bersama.
Re;torika, sebuah grup music indie yang dulunya bernama Sympolite, menawarkan sajian cukup mengajak kita kembali menilik banyak hal dalam realitas kita dalam masyarakat. Grup music yang digawangi oleh Mahendra Perry William, Bekti Al-Ghifari dan Pepe Ivanesz serta Adira R. v. ini menyatakan tidak memiliki kilbat aliran atau genre musik yang pasti, tapi lebih mengutamakan lirik-lirik yg disampaikan. Hal ini terbukti dalam beberapa judul lagu mereka yang banyak bercerita tentang kegelisahan atas realita kehidupan yang mungkin sebetulnya adalah kegelisahan kita semua, khususnya warga +62.
Dalam single Lorong Sepi (https://youtu.be/iKlL8-92L4M?si=ZfNI_bdKdXBbMzAH), Re;torika seolah sedang membangun kesadaran tentang bagaimana kekuasaan kerap digambarkan sebagai sebuah absurditas yang nyaris satir: janji-janji berulang terdengar seperti lelucon yang kehilangan makna, sementara realitas hidup tetap berjalan di tempat. Dari sana lahir rasa muak generasi yang tumbuh menyaksikan siklus politik yang tak kunjung berubah, membuat harapan perlahan bergeser menjadi sinisme, apati, dan humor gelap sebagai mekanisme bertahan. Kritik politik tidak lagi selalu hadir dalam teriakan atau seruan heroik, melainkan dalam nada getir, lirik sinis, dan kepasrahan yang jujur, seolah mengakui kelelahan kolektif menghadapi drama kekuasaan yang itu-itu saja. Kelelahan psikologis dan emosional atas kondisi politik (political fatigue) adalah kondisi kelelahan yang muncul akibat akibat paparan isu politik yang terus berulang tanpa perubahan nyata, sehingga memicu kejenuhan, sinisme, dan apati. Secara sosial, political fatigue tidak selalu berarti ketidakpedulian total terhadap politik, melainkan bentuk perlindungan diri dari stres kolektif dan penanda bahwa ada jarak antara harapan masyarakat dan realitas politik yang mereka alami. Ia juga menjadi sinyal peringatan bahwa ketika politik gagal memberi rasa makna dan keadilan, warga akan mencari ruang lain yang dianggap lebih manusiawi dan jujur untuk menyalurkan kritik dan kegelisahan mereka. Re;torika kemudian memilih musik sebagai ruang aman untuk menampung kelelahan itu, tempat kekecewaan boleh diendapkan tanpa harus berpura-pura optimis, sekaligus menjadi pengingat bahwa di balik sikap pasrah itu, kesadaran kritis mereka masih tetap hidup. Top of Form
Lirik-lirik yang diusung Re;torika juga hadir sebagai ruang aman tempat kelelahan, kecemasan, dan kerapuhan akhirnya bisa diakui tanpa rasa malu. Di tengah masyarakat yang memuja ketangguhan semu, selalu kuat, selalu produktif, selalu baik-baik saja, musik justru memberi jeda untuk berkata bahwa tidak apa-apa merasa runtuh. Netizen Nyinyir (https://youtu.be/Xy4qBAg2Zxo?si=heuStkRIpb9ZptaO), memberi gambaran bagaimana media sosial berubah menjadi ruang penghakiman massal yang riuh, tempat komentar pedas, stigma, dan praktik penggalangan dukungan (cancel culture) menjelma menjadi bentuk kekerasan simbolik yang dianggap lumrah, bahkan menghibur. Liriknya menyuarakan kelelahan menghadapi nyinyir yang terus-menerus, sekaligus menjadi perlawanan sunyi terhadap normalisasi kebencian yang dibungkus kebebasan berekspresi.
Sementara itu, Teman Sialan (https://youtu.be/9Nn0IbHJtyc?si=3WPmZAR6jEpAGpfq) menggeser kritik ke ranah relasi personal, menyoroti sosok teman yang berubah menjadi parasit emosional yang menguras energi, memanfaatkan empati, dan berlindung di balik budaya “nggak enakan” yang memerangkap individu dalam hubungan toksik. Lagu ini hadir sebagai bentuk validasi untuk berani membuat batasan dan memutus relasi yang merusak, sekaligus mengkritik romantisasi solidaritas palsu yang sering dipaksakan atas nama kebersamaan, padahal justru melukai kesehatan mental. Lirik-liriknya menjadi kritik halus terhadap budaya yang menekan emosi demi citra, sekaligus menawarkan bahasa alternatif tentang kesehatan mental yang lebih manusiawi, jauh dari jargon psikologis yang kadang terasa dingin dan berjarak. Melalui musik, luka tidak harus segera disembuhkan atau dijelaskan, cukup didengarkan dan diterima sebagai bagian dari pengalaman hidup. Top of FormBottom of Form
Balada Pulang Kampung (https://youtu.be/LIqY-gKwDRs?si=7_GV6zMb6WkcgYKX) menjadi single yang juga cukup menarik untuk diulas. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa pulang kampung, kerap hadir bukan sekadar sebagai perjalanan pulang, melainkan ritual sosial yang sarat tuntutan dan pertanyaan klasik; kerja apa, kapan nikah, sudah sejauh apa disebut sukses. Pertanyaan-pertanyaan yang pelan-pelan menggerus rasa nyaman. Kampung halaman digambarkan sebagai ruang yang ambivalen: penuh nostalgia dan kenangan hangat, namun sekaligus menjadi arena penghakiman yang mempertanyakan identitas personal berdasarkan standar sosial yang sempit. Konflik antara siapa diri kita sebenarnya dan apa yang diharapkan masyarakat terasa makin tajam, terutama bagi kelas menengah yang bekerja keras namun hidup dalam kecemasan yang tak pernah benar-benar reda. Re;torika, dalam single ini muncul sebagai suara jujur generasi yang jarang diwakili untuk mengungkap kegamangan hidup yang tak selalu bisa dijelaskan dengan angka penghasilan atau status sosial.
Re;torika dengan diksi mereka yang lugas, dan kadang terasa tidak sopan dalam lagu-lagu indie bukan sekadar gaya, melainkan sikap politis yang menolak kepura-puraan bahasa formal dan moral palsu yang sering menutupi kenyataan. Ketidaksopanan itu justru menjadi bentuk kejujuran emosional, cara paling jujur untuk mengekspresikan marah, lelah, dan kecewa tanpa dibungkus etika semu yang menenangkan tetapi menipu. Dari sanalah lagu-lagu ini menjadi relevan dan viral, bukan semata karena algoritma, melainkan karena resonansi emosional yang kuat. Ia hadir sebagai cermin bagi perasaan yang sulit diucapkan, membuat pendengarnya merasa relate dimana akhirnya ada suara yang mewakili kegelisahan mereka tanpa perlu berpura-pura baik-baik saja.
Pada akhirnya, kita memang perlu menyadari bahwa deretan lagu-lagu ini memang bukanlah solusi atas problem sosial yang kita hadapi, melainkan pengingat yang jujur bahwa ada kegelisahan bersama yang tak boleh diabaikan begitu saja. Lagu-lagu itu menjadi ruang refleksi kolektif, tempat emosi personal bertemu kesadaran sosial dan membentuk keberanian untuk mengakui bahwa ada yang perlu dibenahi. Melalui tulisan ini, kritik yang lahir dari lirik-lirik tersebut diupayakan untuk diperpanjang nafasnya, agar tidak berhenti sebagai latar di playlist, tetapi terus hidup sebagai percakapan, kesadaran, dan kemungkinan perubahan.
Mojowarno Jombang, 10 Januari 2026
Oleh: Riris D. Nugrahini seniman aktivis isu-isu perempuan dan guru PAUD Mojowarno Jombang